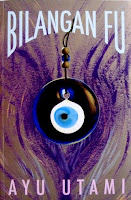TAK banyak pemeluk agama yang mau melakukan otokritik terhadap praktik beragamanya. Tetapi Ayu Utami, penulis novel “Bilangan Fu” berani melakukan itu.
TAK banyak pemeluk agama yang mau melakukan otokritik terhadap praktik beragamanya. Tetapi Ayu Utami, penulis novel “Bilangan Fu” berani melakukan itu.Kenapa monoteisme begitu tidak tahan pada perbedaan? Ia memulai otokritik dengan pertanyaan ini. Sebab kecenderungan ini begitu kuat pada agama-agama Semit, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam.
‘’Bahwa ada dalil-dalil yang mendasari sikap anti terhadap nilai lain (“anti-liyan”) harus diakui sebagai persoalan mendasar monoteisme. Kita harus berani mengakui bahwa monoteisme berkehendak memonopoli kebenaran.’’ tulisnya.
Kehadiran dalil-dalil “anti-liyan” sangat mencolok dalam monoteisme, terutama jika dibandingkan dengan agama-agama yang tumbuh di Asia Tengah sampai ke Timur seperti Hindu, Buddha, Tao, Konghucu, Shinto. Agama-agama ini memiliki sistem yang sangat berbeda dengan monoteisme, dan sangat sulit dimengerti oleh kaum monoteis ortodoks.
Pada “Bilangan Fu”, kita menemukan semacam hipotesis yang ingin menjawab pertanyaan mengapa monoteisme cenderung “anti-liyan”.
Perbedaan mendasarnya, kata penulis buku ini, terdapat pada bilangan yang dijadikan metafora bagi inti falsafah masing-masing. Agama-agama timur sangat menekankan konsep ketiadaan, kekosongan, sekaligus keutuhan. Konsep ini ada dalam kata sunyi, suwung, sunyat, shunya. Konsep ini ada pada bilangan nol. Sebaliknya, monoteisme menekankan bilangan satu. Tuhan mereka adalah SATU. Demikian hipotesisnya.